Rasanya kita selalu “dipaksa” menerima apa saja setiap hari. Soal paham atau tidak itu urusan masing-masing.
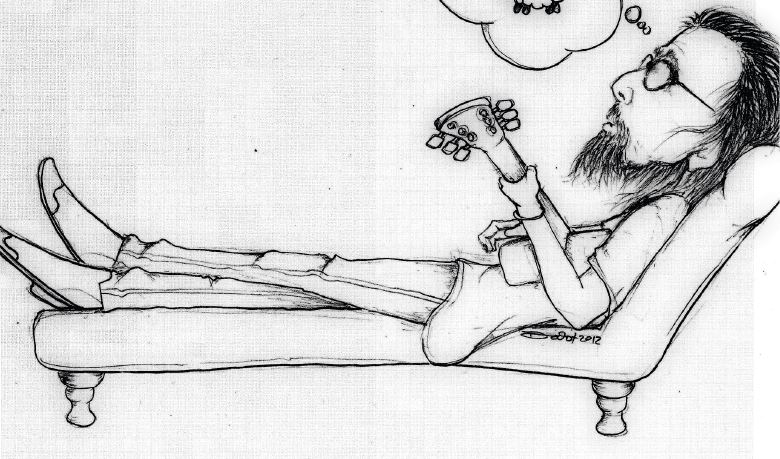
Suatu ketika saya duduk semeja, makan malam bersama Pak Goenawan Mohamad, Pak Endo Suanda, Mas Wahyudin, dan rekan-rekan lain. Nama besar Goenawan Mohamad sudah saya kenal sejak semasa kuliah, 2000an awal. Baru kali ini mendapat kesempatan lebih intim dengan beliau untuk ngobrol, kurang lebih sekitar 2,5 jam. Cukup lama untuk situasi yang intim.
“Perjodohan” ini berkat tawaran Pak Endo, “bos” saya di Majalah Gong dulu (2008-2010). Sebetulnya pertemuan kami berdua sudah berlangsung sejak sore di “Museum dan Tanah Liat”, Bantul. Kami memang sudah lama tidak berjumpa, maka untuk melepas rindu Pak Endo mengajak saya lanjut makan malam. Saya menyanggupi dengan senang hati.
Di meja makan itu banyak cerita dialirkan begitu saja. Sejujurnya saya lebih banyak menjadi pendengar pasif, itu pun sudah enak minta ampun. Sesekali saja menanggapi.
Ada satu cerita yang bikin saya penasaran, yaitu soal “pemahaman” dan “penerimaan”.
Singkat cerita waktu itu kami sedang mengobrolkan Catatan Pinggir (Caping), yang rutin ditulis mingguan di Majalah Tempo oleh Pak Goen. Pertanyaan yang muncul: “Apakah generasi milenial saat ini masih mau membaca Caping? Apakah mereka paham?”
Nama Hairus Salim kemudian nongol. Konon, menurut beliau—yang notabene juga penulis senior yang saya hormati—Caping relatif sulit dipahami, tapi Pak Salim merasa menyukai atau menikmatinya. Dan beliau juga menyampaikan bahwa milenial saat ini “ada” yang baca caping.
Diskusi menjadi lebih rumit ketika memperbincangkan bahwa suatu objek yang kita lihat, baca, pandang, temui, dan lain sebagainya, memang tidak selalu harus “dipahami”—dalam pengertian sampai ke meaning, sampai ke pemaknaan. Ketika orang sudah menyukai atau menikmatinya, sebetulnya itu sudah cukup.
“Saya tidak paham, tetapi suka.” Mungkin kita cukup sering mendengar kalimat itu.
Lalu saya iseng tanya kepada Pak Goen.
“Lalu Pak Goen, kalau Pak Goen menulis caping itu apakah ada target, atau katakanlah keinginan, agar tulisan Pak Goen dipahami?”
Semua mendadak tertawa.
“Haha, benar juga? Gimana Pak Goen?” Mas Wahyudin menyaut, menegaskan pertanyaan saya.
“Ya, kadang-kadang. Tapi sering tidak memiliki target itu. Saya menulis saja. Haha.” Jawab Pak Goen dengan sedikit terkekeh.
Seketika saya ingat tentang musik kontemporer.
Kami di komunitas seringkali memperbincangkan bagaimana musik kontemporer harus “hidup” di telinga masyarakat. Artinya, apakah masyarakat dituntut untuk memahami bunyi-bunyian yang konon jauh lebih rumit seribu kali lipat ketimbang musik pop itu? Namun pikiran saya sudah lama sadar, bahwa ketika saya menonton (mendengar) pertunjukan musik kontemporer, sudah sejak dari rumah “tidak ingin punya target memahami.” Menyukai saja sudah bersyukur. Tapi anehnya, banyak juga teman yang trauma bunyi kontemporer. Tak mau lagi dengar musik kontemporer. Alasannya? Sederhana: bikin pusing dan muntah.
Begitulah. Memang rasanya kita “selalu dipaksa menerima apa saja” setiap hari. Soal paham atau tidak itu memang urusan masing-masing.