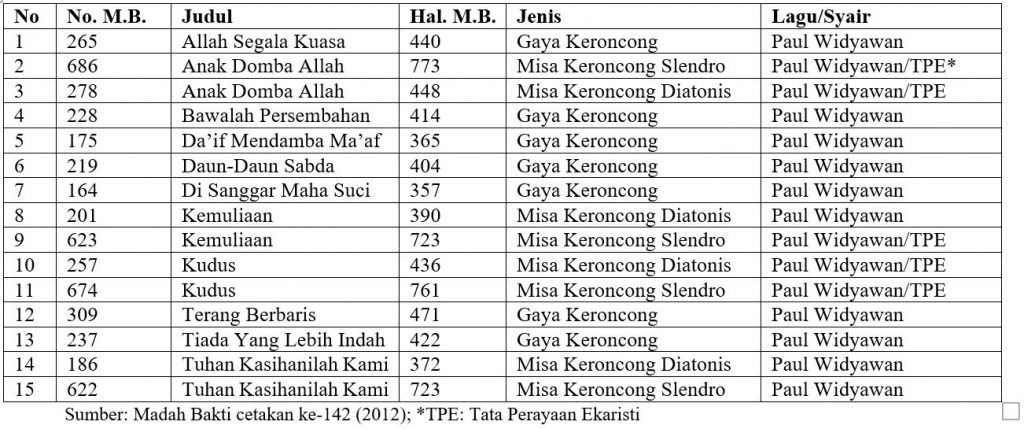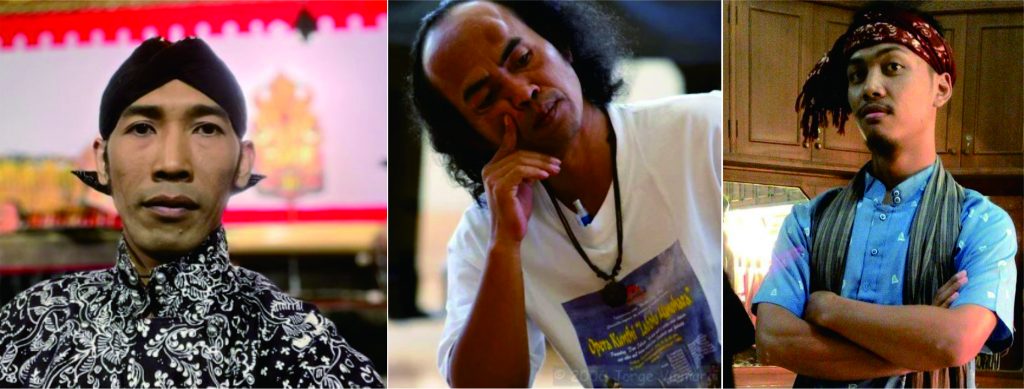Remy Sylado menyebut Suka Hardjana sebagai seorang dengan empat identitas: musikus, pedagog, pemikir, dan penulis musik.
“Seperti petani, lahanku kecil, tapi harus diolah dengan sabar, telaten, agar tumbuh tunas muda.”
Bagi Suka Hardjana, hampir setiap malam selama puluhan tahun adalah gundah-gelisah tak berkesudahan. Lelaki Jawa kelahiran Jogja ini punya jadwal rutin termangu di depan mesin ketik, lalu menuliskan ide-ide, membayangkan masa depan. Sesekali menyentuh tuts piano lawas koleksinya sambil bernyanyi lirih, atau cukup mendengarkan musik klasik dari telefunke.
Dituliskannya nama-nama, sejarah, peristiwa, momen-momen, dalam sudut pandang yang seringkali tak terpikirkan orang. Namanya mulai sering muncul di koran-koran sejak 1972, hingga tiba fase produktivitas yang menyurut pada 2004 dan sesudahnya. Sedikitnya 30 tahun pemikirannya yang khas mewarnai ulasan-ulasan musik di lembar-lembar opini media massa Meski diakuinya: “Menulis adalah kecelakaan sejarah.” Pernyataan itu disampaikan kepada putra semata wayangnya yang kini menjadi dosen sosiologi di Jerman. Suka (merasa) “gagal” menjadi musikus tersohor, seperti dicita-citakannya sejak remaja.
Dalam karir kepenulisan yang dianggapnya sebagai kecelakaan itu, ia malah merambah ke topik-topik di luar musik, seperti politik, sosial, hukum, dan kebudayaan. Selama sekian tahun ia dipercaya sebagai kolumnis untuk Kompas, nangkring bergantian bersama Harry Roesli dan Mohamad Sobary, membahas berbagai dinamika kehidupan masyarakat dengan bahasa yang kritis, lugas, sederhana, namun esensial. Hasil buah pikirannya tersebut dikumpulkan menjadi dua buku terpisah: Jas, Wakil Rakyat, dan Tiga Kera: Percikan Kebijaksanaan (Kompas, 2008), Prof. Dr. Miecky Mouse dan Human Error: Percikan Kebijaksanaan (Laras, 2017).
Sabtu, 7 April 2018 pukul 3 dini hari, Suka Hardjana wafat di RS Cikini, Jakarta karena sakit, pada usia 79 tahun. Jenazahnya dibawa ke Solo via jalur darat dan kemudian dimakamkan di TPU Triyagan, Jaten, Karanganyar. Pemakaman dihadiri oleh kolega-kolega dekatnya, para seniman dan akademisi: Sal Murgiyanto, Endo Suanda, Bre Redana, Rahayu Supanggah, Sutanto Mendut, Djohan Salim, dan lain-lain.
Seluruh rencana yang tengah disusun untuk kelak memperingati 80 tahun usianya pada 17 Agustus 2018 mendatang—terutama penerbitan buku biografi yang rencananya sebagai kado ulang tahun—seketika buyar, berganti ratapan. Istri Suka, Mugiyarsi, sangat menyesali kenyataan ini, karena ialah yang paling mengidam-idamkan momen spesial untuk suaminya ini. Sementara itu, pianis senior segenerasi dengan Suka, Iravati Sudiarso, masih tetap ingin mempersembahkan sesuatu kepada almarhum pada Agustus nanti, berupa pertunjukan musik.

Sosok Figur Lengkap
Suka Hardjana adalah gelora api yang terus membara hingga detik ini, dan akan terus berkobar sepanjang musik dan pengetahuan bersemayam di batin manusia. St Sunardi, dosen di Program Doktor Kajian Budaya (Kajian Seni dan Masyarakat) menyebut Suka sebagai jembatan emas yang menghadirkan musik sebagai pengetahuan dan ilmu. Tidak sekadar bunyi-bunyian yang kemudian hilang tanpa warisan.
Ia menempuh perjalanan panjang dan serius demi meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap musik. Oleh para kolega, hidupnya dikenal lurus, tidak aneh-aneh, penuh karya, menerangi, dan yang penting: memberi contoh.
Pada usia senja dengan kualitas syaraf pendengaran dan detak jantung yang terus melemah, ia masih ditodong ke sana-sini untuk berceramah maupun membimbing mahasiswa musik, meladeni sepenuh hati.
Sosoknya yang tangguh adalah figur yang lengkap piranti keterampilan dan pengetahuan musiknya, layaknya Amir Pasaribu, Slamet Abdul Sjukur, Ben Pasaribu, Sapto Raharjo, Harry Roesli, dan sekian tokoh musik garda depan berpengaruh lainnya yang lebih dulu berpulang.
Dari tangan dingin Suka banyak orang bisa menyaksikan bagaimana perjalanan musik Indonesia dituliskan secara jernih. Kita bisa membaca dalam dua buku utama, arsip tulisan khusus musik di koran-koran yang juga telah menjadi buku: Musik, Antara Kritik dan Apresiasi (Kompas, 2004) yang memuat 82 artikel, serta Esai dan Kritik Musik (Galang Press, 2004) yang memuat 69 artikel. Pemikirannya di dua buku itu sangat sering dikutip untuk keperluan karya tulis.
Satu bulan sebelum wafat, Suka masih menulis sebuah artikel sepanjang 2.058 kata untuk melengkapi buku karangannya, Estetika Musik, sebuah buku yang telah terbit 1983 silam dan diterbitkan ulang pada 2018 karena bobot relevansinya. Sepenggal bagian artikel tersebut seperti sebuah isyarat, membahas kaitan antara gerak dan musik:
“Tubuh terus bergerak sebagaimana bunyi: dan itulah yang disebut sebenar-benarnya musik! Seperti gerak orbit bumi-bulan dan matahari: gerak adalah musik! Bunyi dan gerak adalah kesatuan organik yang tak terpisahkan. Dari sanalah awal-mula dan akhir kehidupan di semesta bumi (AMT, 2018: 162-163).”
Pemikiran terkini (dan terakhir) Suka tersebut menyiratkan sebuah pandangan futuristik mengenai musik. Bahwa intinya dalam segala (yang ber)gerak terkandung musik. Gerak jantung adalah musik, gerak kaki yang meritmis adalah musik, hela nafas, tiupan angin, gerak daun, ombak, dan sebagainya; kendati semua itu seakan “diam” dan tak terdengar begitu saja oleh kemampuan telinga manusia yang terbatas. Tetapi gerak, bagi Suka, telah menjadikan musik ada. Gerak dialami oleh semesta dan isinya, sampai seluruhnya hilang tak lagi menyisakan ruang. Tanpa menyebut diri sebagai pemusik pun, setiap manusia “selalu bermusik” karena fitrahnya.
Pria yang Menempuh Perjalanan Panjang
Selama hidupnya, sosok ini banyak menerima keberuntungan tak terduga. Seperti dikisahkan di buku Manusia Anomali Tanpa Kompromi (2014), di suatu sore tahun 1964, saat Suka sedang mencuci pakaian, datang petugas pos membawa kiriman berisi berkas-berkas. Saat itu ia masih duduk di semester akhir Sekolah Musik Indonesia (SMIND) Yogyakarta. Setelah dibaca, isi berkas-berkas itu menerangkan bahwa Suka telah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan belajar musik ke Jerman. Berita ini tentu saja sangat mengherankan, karena Suka tidak pernah sekalipun mengajukan lamaran.
Usut punya usut, kejutan ini adalah “ulah” dari Rene Baumgartner, guru klarinetnya semasa di SMIND. Ia diam-diam merekomendasikan Suka untuk mendapat beasiswa belajar klarinet. Suka hanya memiliki kesempatan beberapa hari untuk pergi ke Jakarta mengurus keberangkatan. Ia tidak mempersiapkan apa-apa dengan matang, hanya membawa empat potong pakaian, klarinet, dan beberapa buku. Koper bagus yang dibawanya pun adalah pemberian Rene, gurunya yang mulia itu.
Keberuntungan kedua hampir sama ceritanya. Kali ini Suka ketiban berkat melanjutkan kembali studi conductorship (ilmu mengaba) di Ohio, Amerika. Juga melalui beasiswa yang tanpa melamar. Yang kedua ini karena “rayuan” Paul Wolfowitz, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Di Amerika itu Suka juga berkesempatan belajar manajemen seni. Zona pergaulannya semakin luas, dan tentu saja pengetahuannya semakin lengkap karena kesempatan demi kesempatan itu.
Sepulang dari rangkaian perjalanan luar negeri, Suka kemudian berkarya di Indonesia. Ia terus-menerus mendapat keberuntungan–yang sebenarnya adalah hasil tak langsung dari kerja keras dan dedikasinya.
Suka turut membidani berdirinya LPKJ (Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta) yang sekarang menjadi IKJ (Institut Kesenian Jakarta), terutama memikirkan program studi musik di sana. Ia kemudian mendirikan Ensembel Jakarta; menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta—yang kemudian menginisasi Pekan Komponis Muda mulai 1979; mendirikan Klinik Musik Suka Hardjana: Pusat Studi dan Orientasi Musik—Suka rutin memberi bimbingan kepada para jurnalis musik; mengajar untuk program pascasarjana di kampus seni; menjadi kolumnis—adalah sebagian besar jejak penting pengalaman Suka di tanah air.
Remy Sylado (1992: 194), menyebut Suka Hardjana sedikitnya punya empat identitas kunci: musikus, pedagog, pemikir, dan penulis musik. “Dalam memandang musik, ia kritis dan realistis,” kata Remy. Suka juga tidak memandang remeh musik-musik lain selain yang ia tulis.
“Suka termasuk salah seorang pemikir musik yang baik yang pernah dipunyai Indonesia. Artinya, ia berpikir sebagai orang Indonesia dengan melihat sepenuhnya kepentingan Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain,” lanjut Remy. Idris Sardi, violinis kenamaan yang juga sahabat dekatnya, menilai Suka adalah orang yang mau bersusah-susah, supaya orang lain ketiban “suka-nya.”
Namun rasanya banyak yang mengatakan Suka Hardjana seakan “gagal” melahirkan generasi penulis musik dalam kapasitas yang lengkap, terutama yang sering disebut kritikus—meski Suka sendiri tak pernah mau mengakui bahwa dirinya adalah kritikus musik. Memang benar, apa yang selama ini dilakukan Suka Hardjana tidak selalu paralel dengan stereotipe yang beredar.
Apalagi di Indonesia, profesi kritikus musik kurang mendapat tempat dan pengakuan. Area kerjanya masih serba abu-abu, masih terasa asing di telinga masyarakat. Suka menyebut dengan tegas: “ada kesenjangan antara kritik, karya seni, dan masyarakat pendukungnya” (2004: xv).
Suka hanya bermodal ketulusan dan kecintaan bahwa apa yang selalu ditulisnya (ia juga percaya) akan menjadi faedah di masa mendatang, terutama bagi tunas muda yang silih berganti mewarnai dinamika musik dari hari ke hari. Maka, sekiranya kita juga perlu lebih pandai dalam memetik pelajaran penting dari tokoh satu ini, bukan hanya soal “kata-kata pedas” yang sering mengalir di tulisannya, melainkan harga sebuah dedikasi untuk generasi. Apakah kita mampu menulis tanpa henti selama 30 tahun?
Suka Hardjana berhasil mengangkat derajat peristiwa musik hingga menjadi sebuah pengetahuan yang abadi—dinikmati oleh berbagai generasi, lebih dari sekadar euforia dan caci-maki antar sesama yang mewarnai hari-hari kita saat ini.
Selamat jalan, Pak Suka. Sungkem dari saya.
//
Artikel ini telah dimuat sebelumnya di tirto.id (22 April 2018). Atas pemuatan artikel ini saya menghaturkan terimakasih kepada Mas Nuran Wibisono.